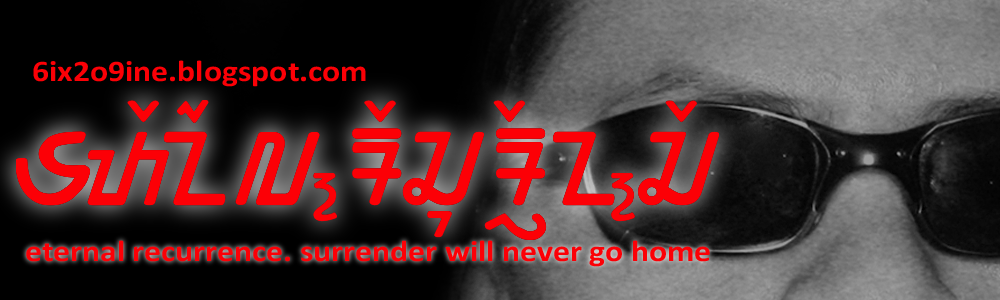Seks menjadi hal yang tabu dibicarakan di masa lalu. Selain karena berhubungan dengan kehormatan, juga bila dilakukan tidak dengan pasangan resmi akan menjadi kisah perzinahan alias skandal.
Hal tersebut disadari penting oleh penulis naskah kuno Carita Parahiangan. Naskah yang menggunakan huruf Sunda Kuno dan bahasa Sunda Kuno itu dengan gamblang mengungkap perzinahan yang dilakukan raja, juga 'prameswari' permaisuri. Bahkan anak hasil zina pun turut mewarnai sejarah perebutan kekuasaan di antara urang Sunda di masa ratusan tahun silam.
VI. Ngareungeu tatabeuhan humung gumuruh tanpa parungon, tatabeuhan di Galuh. Pulang ka Galuh teter nu ngigel.
Sadatang ka buruan ageung, carék Rahiyangtang Mandiminyak, "Sang Apatih, na saha éta?" "Béjana nu ngigel di buruan ageung." "Éta bawa sinjang saparagi, iweu kéh pamalaan aing. Téhér bawa ku kita keudeukeudeu!"
Leumpang sang apatih ka buruan ageung, dibaan ka kadatwan na Pwah Rababu. Dipirabi ku Rahiyangtang Mandiminyak, dirabi kasiahan na Pwah rababu. Diseuweu patemuan, dingaranan Sang Salah.
Carék Rahiyang Sempakwaja, "Rababu leumpang! Ku siya bwatkeun budak éta ka Rahiyangtang Mandiminyak. Anteurkeun patemuan siya Sang Salahtwah."
Barang ngadéngé tatabeuhan ngaguruh teu puguh rungukeuneunana, tatabeuhan di Galuh, Pwah Rababu terus mulang ka Galuh di dinya téh taya kendatna nu ngigel.
Sadatangna kaburuan ageung, cek Rahiangtang Mandiminyak: "Patih, na naon éta téh?"
"Béjana nu ngigel di buruan ageung!"
"Éta bawa pakéan awéwé sapangadeg, sina marek ka dieu. Keun tanggungan aing. Geuwat bawa sacara paksa!"
Patih indit ka buruan ageung. Pwah Rababu dibawa ka kadaton. Dipirabi ku Rahiangtang Mandiminyak. Kacida bogohna ka Pwah Rababu. Tina sapatemonna, nya lahir anak lalaki dingaranan Sang Salah.
Carék Rahiang Sempakwaja: "Rababu jig indit. Ku sia bikeun éta budak ka Rahiangtang Mandiminyak, hasil jinah sia, Sang Salahlampah.
Dalam tafsir yang dibuat Oleh Abdurrachman dkk dalam "Carita Parahiangan: Ringkasan, Konteks Sejarah Isi Naskah dan Peta" (1990) disebut bila Mandiminyak menggauli kakak iparnya, Pwah Rababu atau disebut di naskah Wangsakerta sebagai Dewi Wulansari. Adapun suami sah Dewi Wulansari adalah Sempakwaja, kakak kandung Mandiminyak.
Hasil perzinahan itu menyebabkan Dewi Wulansari hamil dan lalu melahirkan seorang anak yang diberi nama Sang Salah atau Sang Sena.
Perhatikan: Dalam transkripsi naskah disebut Sang Salah atau Salahlampah sedang dalam transliterasi oleh Atja disebut sebagai Sang Sena.
Begitu juga dalam tafsir Abdurrachman dkk, bila di transkripsi dan transliterasi naskah disebut Pwah Rababu Dalam tafsir disebut Pwah Rababu itu Dewi Wulansari. Kisah ini diperkirakan terjadi di masa kekuasaan Wretikandayun antara 670-702 M.
Kelak Sang Salahlampah atau Sena atau Bratasena ini akan menjadi Raja Galuh dengan gelar Sang Senna Rajaputra Linggabhuwana menggantikan ayahnya, Mandiminyak.
Sang Sena ini pula yang kelak memiliki seorang anak bernama Sanjaya, yang kelak menjadi pendiri kerajaan Medang Mataram Kuno pada tahun 732 M. Candi Prambanan adalah salah satu peninggalan Wangsa Sanjaya yang beragama Hindu.
 |
| Peta Bogor lama buatan VOC tahun 1701 yang masih memuat lokasi kerajan Pajajaran. |
Skandal seks lainnya dalam kronik sejarah Sunda masih berlanjut di keturunan Sanjaya. Disebut bila setelah Sanjaya menjadi Raja Galuh dan Raja sunda, memilih ia berdomisili ibukota karajaan Sunda, di wilayah yang kita kenal sekarang sebagai Bogor.
Sedangkan Galuh, tepatnya di wilayah yang kita kenal sebagai Kawali Ciamis, dikuasakan pada Prabu Permanadikusumah sebagai raja taklukan. Untuk mengawasi kinerja sang prabu, ditempatkanlah Raden Anom Barmawijaya atau Rahyang Tamperan yang berstatus sebagai duta patih atau wakil raja.
Ternyata Barmawijaya ini tergoda pada Dewi Pangrenyep, istri kedua Prabu Permanadikusumah. Di suatu hari di saat Prabu Permanadikusumah sedang bertapa, Bramawijaya menggoda Dewi Pangrenyep hingga terjadi perzinahan.
Dari perzinahan itu lahirlah seorang bayi laki-laki yang bernama Raden Kamarasa atau Dang Arya Banga. Atau di dalam naskah Carita Parahiangan disebut sebagai Rahiyang Banga.
Dalam tradisi lisan masyarakat Sunda Rahiyang Banga ini disebut sebagai Hariang Banga, Ia adalah tokoh antagonis yang bersebrangan dengan Sang Manarah atau dikenal sebagai Ciung Wanara atau Sang Surotama. Sang Manarah ini adalah kakaknya beda ibu, dari istri pertama Prabu Permanadikusumah yakni Dewi Naganingrum.
Tradisi lisan Ciung Wanara ini diperkirakan benar terjadi di abad ke-7 . Yakni perebutan kekuasaan antara kakak beradik, Hariang Banga melawan Ciung Wanara yang kemudian dimenangkan oleh Ciung Wanara.
Hariang Banga kemudian menjadi raja di Kerajaan Sunda, sedangkan Sang Manarah menjadi raja di Kerajaan Galuh. Kisah ini diperkirakan terjadi tahun 723 - 740 M.
XV. Tembey Sang Resi Guru ngayuga taraju Jawadipa, taraju ma inya Gulunggung, Jawa ma ti wétan.
Di pamana Sunda hana pandita sakti, ngaraniya Bagawat Sajalajala, pinejahan tanpa dosa. Mangjanma inya Sang Manarah, anak Rahiyang Tamperan, dwa sapilanceukan denung Rahiyang Banga.
Sang Manarah males hutang; Rahiyang Tamperan sinikep deneng anaknira. Ku Sang Manarah dipanjara wesi na Rahiyang Tamperan. Datang Rahiyang Banga, ceurik, teher mawakeun sekul kana panjara wesi, kanyahoan ku Sang Manarah. Tuluy diprangrang deung Rahiyang Banga. Keuna mukana Rahiyang Banga ku Sang Manarah.
Ti inya Sang Manarah adeg ratu di Jawa pawwatan.
Carék Jawana, Rahiyang Tamperan lawasniya adeg ratu tujuh tahun, kena twah siya bogoh ngarusak nu ditapa, mana siya hanteu heubeul adeg ratu.
Sang Manarah, lawasniya adeg ratu dalapanpuluh tahun, kena rampés na agama. Sang Manisri lawas adeg ratu geneppuluh tahun, kena isis di Sanghiyang Siksa. Sang Tariwulan lawasniya ratu tujuh tahun. Sang Welengan lawasniya ratu tujuh tahun.
Mimiti Sang Resi Guru ngawangun kuta pulo Jawa, kutana téh nya éta Galunggung, ti wétana Jawa.
Di wates Sunda, aya pandita sakti, dipaténi tanpa dosa, ngaranna Bagawat Sajalajala. Atma pandita téh nitis, nya jadi Sang Manarah. Anakna Rahiang Tamperan duaan jeung dulurna Rahiang Banga.
Sang Manarah males pati. Rahiang Tamperan ditangkep ku anakna, ku Sang Manarah. Dipanjara beusi Rahiang Tamperan téh.
Rahiang Banga datang bari ceurik, sarta mawa sangu kana panjara beusi téa. Kanyahoan ku Sang Manarah, tuluy gelut jeung Rahiang Banga. Keuna beungeutna Rahiang Banga ku Sang Manarah.
Ti dinya Sang Manarah ngadeg ratu di Jawa, mangrupa persembahan.
Nurutkeun carita Jawa, Rahiang Tamperan lilana ngadeg raja tujuh taun, lantaran polahna resep ngarusak nu tapa, mana teu lana nyekel kakawasaanana ogé.
Sang Manarah, lilana jadi ratu dalapanpuluh taun, lantaran tabéatna hadé. Sang Manisri lilana jadi ratu genep puluh taun, lantaran pengkuh ngagem Sanghiang Siksa. Sang Tariwulan lawasna jadi ratu tujuh taun.Sang Welengan lawasna jadi ratu tujuh taun.
Tidak hanya itu, skandal juga membuat Raja Galuh jatuh dari kekuasaannya. Raja Galuh yang disebut dalam bagian ke-18 naskah Carita Parahiangan hanya berkuasa 7 tahun saja karena mencintai istri larangan.
XVIII. Tohaan di Galuh, inya nu surup di Gunungtiga. Lawasniya ratu tujuh tahun, kena salah twah bogoh ka éstri larangan ti kaluaran.
Diganti ku Tohaan Galuh, enya éta nu hilang di Gunungtiga. Lawasna jadi ratu tujuh taun, lantaran salah tindak bogoh ka awéwé larangan ti kaluaran.
Kalau disesuaikan dengan tafsir Abduracman dkk yang berdasar Wangsakerta, bila Tohaan di Galuh yang dimaksud sepertinya adalah Prabu Dewa Niskala. "Pada tahun 1404 Saka (1482/1483 Masehi) Kerajaan Galuh berkabung. Raja Galuh Prabhu Dewa Niskala meninggal dunia, setelah berkuasa selama 7 tahun," tulisnya.
***
Selain itu, masih ada lagi skandal cinta yang terjadi. Kali ini adalah antara Prabu Geusan Ulun, yang memerintah Sumedang selama 23 tahun dari 1578-1601 M, dengan Ratu Harisbaya. Prabu Geusan Ulun pada saat itu sudah memiliki prameswari yakni Nyi Mas Cukang Gedeng Waru. Sedangkan Harisbaya adalah istri ke dua Sultan Cirebon, Panembahan Ratu 1.
Sebelumnya di masa mudanya, Geusan Ulun atau Pangeran Angkawijaya pernah menjalin hubungan dengan Harisbaya. Yakni saat mereka masih belajar di Kerajaan Pajang menjadi Murid Sultan Hadiwijaya atau Joko Tingkir. Harisbaya adalah putri Madura yang mengabdikan diri dan magang di Kerajaan Pajang.
Usai sebuah pertemuan di Cirebon, Geusan Ulun melarikan Harisbaya yang saat itu sedang hamil muda. Akibatnya terjadi peperangan antara Kerajaan Sumedang Larang dan Kasultanan Cirebon. Perang tersebut berlangsung selama tiga tahun dan baru berhenti setelah adanya ikrar perdamaian. Sumedang Larang akhirnya menyerahkan sebagian wilayahnya, yakni Sindangkasih Majalengka, untuk 'membeli' talak dari Panembahan Ratu 1 untuk Ratu Harisbaya.
Ricky N. Sastramihardja
📷 Ilustrasi Bing AI Generated, Peta Cornelis Coops & Michiel Rams/VOC. 1701. Natioonal-Archief
Referensi:
1. Naskah Carita Parahyangan. Dedi Kusmayadi Soerialaga. Academia.edu, diakses 3 Januari 2025. https://www.academia.edu/45578452/NASKAH_CARITA_PARAHYANGAN
2. CARITA PARAHIANGAN Ringkasan, Konteks Sejarah Isi Naskah dan Peta. Abdurrachman, Eti RS, Edi S. Ekadjati. Yayasan Pembangunan Jawa Barat Tim Pengembangan Naskah Wangsakerta. 1990. Versi digital, diakses 4 Januari 2025. https://sundadigi.com/bacaan/detail/125
3. Perbedaan Wangsa Sanjaya dan Wangsa Syailendra. Verelladevanka Adrymartanino, Tri Indriawati. Kompas.com, 22 Februari 2023. Diakses 6 Januari 2025. https://www.kompas.com/stori/read/2023/02/22/180000979/perbedaan-wangsa-sanjaya-dan-wangsa-syailendra
4. Kisah Prabu Geusan Ulun, Pesonanya Membuat Ratu Harisbaya Rela Mati dan Tinggalkan Takhta. Anicolha. SINDONews, 24 Juni 2022. Diakses 6 Januari 2025. https://daerah.sindonews.com/read/806981/29/kisah-prabu-geusan-ulun-pesonanya-membuat-ratu-harisbaya-rela-mati-dan-tinggalkan-takhta-1655993198
5. Sejarah Singkat Raja Sumedang Larang Prabu Geusan Ulun. Sabtu, 7 Mei 2011. TarungNews, diakses 6 Januari 2025. https://www.tarungnews.com/profile/2497/sejarah-singkat-raja-sumedang-larang-prabu-geusan-ulun.html
6. KISAH CINTA SEGITIGA, Ratu Maha Cantik Harisbaya, Panembahan Ratu dan Geusan Ulun. Rahman Prayitno Sodikin/Portal Majalengka, 26 Mei 2024. Diakses 6 Januari 2025. https://portalmajalengka.pikiran-rakyat.com/khazanah/pr-838133689/kisah-cinta-segitiga-ratu-maha-cantik-harisbaya-panembahan-ratu-dan-geusan-ulun?page=all